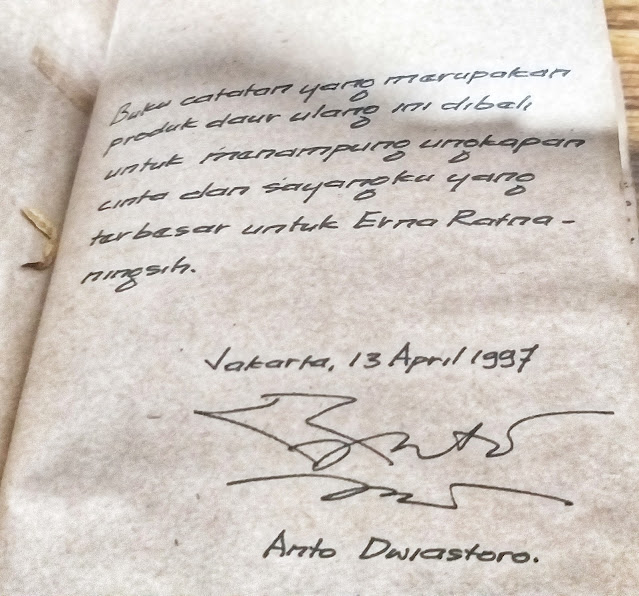|
| Ibu saya di India, 1960. |
Tahun 2006, saya baru tahu siapa leluhur saya dari garis ibu. Ibu saya orang Aceh kelahiran Langsa dan dibesarkan di Meulaboh, dengan wajah menyerupai wanita India. Saya pun mewarisi kemiripan dengan beliau, sehingga tak sedikit yang mempertanyakan mengapa nama saya terkesan Jawa tapi wajah bernuansa Melayu-India. Salah satu yang menanyakan hal itu adalah alm. Pak Muchtaruddin Siregar, mantan Ketua Umum PPK Subud Indonesia. Sebagai orang Tapanuli, beliau langsung menanggapi, “Ooh, pantaslah. Orang kita rupanya!”
Pak Siregar menanyakan hal itu ketika bertemu saya pada jadwal Latihan di S. Widjojo Centre. Saya jelaskan saat itu bahwa kakek saya dari garis ibu berasal dari Barus, sebuah kota emporium dan pusat peradaban pada abad ke-1 hingga ke-7 Masehi. Kini, Barus adalah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sedangkan nenek saya asal Tapanuli Tengah bermarga Pasaribu.
Tetapi adalah alm. Pak Djoko Mulyono, pembantu pelatih sepuh Cabang Jakarta Selatan, yang berkata ke saya, pada tahun 2006, “Saya perhatikan, untuk seseorang yang baru masuk Subud, penerimaan kamu cepat sekali. Saya curiga, leluhur kamu jangan-jangan seseorang dengan latar belakang spiritual yang mumpuni. Mau saya dampingi testing untuk menyusuri garis leluhurmu?”
Walaupun saya penasaran, saya tampik tawaran beliau—saya takut tidak bisa balik, karena yang saya bayangkan adalah bahwa saya akan masuk lorong waktu gaib.
Rupanya penasaran saya terjawab keesokan harinya: Saat menghadiri resepsi pernikahan sepupu saya, saya menjumpai beberapa sesepuh keluarga besar kakek dan nenek saya dari Aceh. Saya pun bertanya ke mereka, dan jawaban mereka juga menjawab kecurigaan Pak Djoko: Akarnya adalah seorang sufi dari Irak berdarah Persia dari garis Syekh ‘Abd al-Qadir al-Jilani, yang dalam perjalanan ke Nusantara (untuk menyebarkan agama Islam) singgah di Gujarat, India, dan menikah dengan wanita lokal.
“Tapi generasi-generasi sesudah beliau sudah tidak lagi mengamalkan tasawuf,” jelas satu sesepuh itu.
Sesepuh itu agak heran mengapa saya
menanyakan asal-usul leluhur, karena menurut beliau generasi muda sudah tidak
peduli dengan leluhur maupun sejarah keberadaan mereka.©2024
Pondok Cabe,
Tangerang Selatan, 27 September 2024